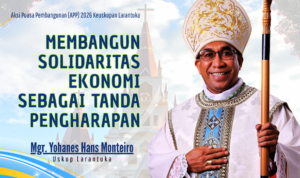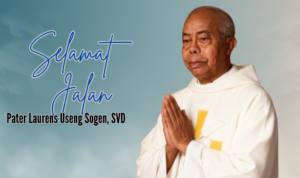Anselmus Dore Woho Atasoge
Kitab Bil. 21: 4 – 9 mengisahkan, di padang gurun, umat Israel yang dipagut ular tedung menemukan harapan dalam tanda yang tak lazim: seekor ular tembaga yang digantung pada tiang. Bukan karena benda itu memiliki kuasa, melainkan karena iman mereka pada sabda Tuhan yang menyembuhkan. Dan, tanda itu menjadi pralambang dari keselamatan yang jauh lebih besar yakni Yesus Kristus yang ditinggikan di kayu salib, yang menjadi sumber penyembuhan bagi dunia yang terluka.
Dalam Surat kepada Jemaat di Filipi (Flp. 2: 6 -11), Rasul Paulus menulis tentang Kristus yang menghampakan diri, merendahkan diri hingga wafat di salib. Justru karena kerendahan dan ketaatan-Nya, Allah meninggikan Dia sebagai Penyelamat umat manusia. Salib bukan sekadar simbol penderitaan, melainkan puncak belaskasih Allah yang menebus dan memulihkan.
Sabda Yesus dalam Injil Yohanes (Yoh. 3: 13 – 17) menjadi inti dari seluruh pewartaan: “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal…” (Yoh. 3:16). Firman ini bukan hanya rumusan teologis, melainkan undangan untuk mengalami kasih yang menyelamatkan. Kasih yang tidak menghakimi, tetapi memulihkan. Dalam konteks sosial yang kompleks, pesan ini menjadi relevan bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi bangsa yang sedang bergumul dengan luka-luka kolektifnya.
Di Indonesia hari ini, kita menyaksikan banyak “padang gurun” yang memagut kehidupan rakyat: banjir bandang di NTT, tanah longsor di Sumatra, krisis pangan di Papua, dan konflik sosial yang meretakkan solidaritas kebangsaan. Dalam semua itu, kita bertanya: di mana tanda penyembuhan? Di mana wajah belaskasih?
Salib Kristus mengajak kita untuk tidak memandang penderitaan sebagai kutukan, tetapi sebagai ruang perjumpaan dengan kasih yang menyelamatkan. Dalam konteks Indonesia, salib menjadi panggilan untuk solidaritas yang konkret. Hal itu menyata dalam hal seperti pemerintah yang rendah hati dan taat pada kebenaran, bukan pada kepentingan politik sesaat; Gereja dan komunitas iman yang tidak hanya berkhotbah, tetapi hadir di tengah korban bencana dan ketidakadilan; serta warga negara yang berani memandang “ular tembaga” zaman ini berupa ‘tanda-tanda kecil harapan’ dan percaya bahwa pemulihan dimulai dari kasih yang aktif.
Ketika kita memandang salib, kita tidak hanya melihat penderitaan, tetapi juga belaskasih yang tak berhingga. Belaskasih yang memulihkan martabat manusia, yang menolak kekerasan, yang membela yang lemah. Dalam konteks Indonesia, belaskasih itu bisa berarti membangun sistem tanggap bencana yang adil dan inklusif, menyuarakan hak-hak masyarakat adat dan korban pembangunan, serta menghidupkan dialog antaragama yang menyembuhkan luka sejarah dan prasangka.
Salib Kristus adalah undangan untuk hal-hal kecil namun berdampak besar. Kita diharapkan untuk menjadi penyembuh, bukan penonton. Untuk menjadi pembawa kasih, bukan penyebar kebencian. Untuk menjadi bangsa yang ditinggikan bukan karena kekuatan ekonomi, tetapi karena kerendahan hati dan keberpihakan pada yang menderita.
Indonesia yang terluka membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan. Ia membutuhkan belaskasih yang hidup dalam tindakan. Mari kita memandang salib bukan sebagai beban, tetapi sebagai jalan menuju pemulihan bangsa. Karena Allah adalah kasih. Dan kasih itulah yang menyelamatkan.
Santo Gregorius Agung, seorang Paus dan pujangga Gereja yang dikenal karena kepemimpinan spiritualnya di tengah krisis sosial dan politik pada abad ke-6. Ia menulis: “Hati yang tidak digerakkan oleh belaskasih bukanlah hati yang mengenal Tuhan.”
Pernyataan ini menegaskan bahwa iman yang sejati tidak berhenti pada doktrin atau kebijakan, melainkan harus menjelma dalam tindakan nyata yang menyentuh penderitaan sesama. Dalam konteks Indonesia, di mana luka-luka sosial dan ekologis terus menganga, belaskasih bukanlah pilihan tambahan melainkan inti dari pemulihan.
Ketika kita berkata bahwa salib bukan beban, melainkan jalan pemulihan, kita mengakui bahwa penderitaan bangsa hanya dapat ditransformasikan melalui kasih yang aktif: kasih yang membela yang tertindas, yang hadir di tengah korban bencana, dan yang menolak untuk tunduk pada ketidakadilan struktural. Santo Gregorius mengingatkan kita bahwa mengenal Tuhan berarti menghidupi kasih-Nya dalam dunia yang konkret dalam kebijakan yang berpihak, dalam solidaritas lintas iman, dan dalam keberanian untuk menyembuhkan luka bangsa.
Dengan demikian, seruan “Allah adalah kasih” bukan sekadar kutipan rohani, tetapi kompas moral bagi bangsa yang ingin bangkit bukan hanya secara ekonomi, tetapi secara kemanusiaan. Kasih itulah yang menyelamatkan. Dan kasih itulah yang harus menjadi denyut nadi Indonesia yang baru.